Wacana yang saya tulis ini berasal dari hasil diskusi
saya bersama kawan saya yang bernama Josman Simarmata terkait dengan munculnya
gerakan populis di Bandung. Dalam diskusi tersebut, Saya sependapat dengan
kawan Josman terkait dengan gerakan populis yang menempatkan tujuan sebagai
subjek sebagai gerakan yang sejati. Tetapi menurut saya, pernyataan tersebut
tidak menyentuh akar permasalahan, mengapa populisme bisa menjadi pisau bermata
dua? Jika dipakai untuk kebaikan akan menghasilkan hal baik dan jika dipakai
untuk keburukan akan menghasilkan hal yang buruk pula.
Gerakan populis yang selama ini kita kenal mempunyai
makna yang dangkal, yaitu gerakan yang mempunyai tujuan untuk bagaimana caranya
meraih simpati rakyat untuk tujuan tertentu. Tentunya gerakan populis tidak
selalu berarti gerakan yang memanfaatkan simpati masyarakat untuk menjadi
popular. Pada kenyataannya, kata ‘populis’ sendiri sudah tereduksi maknanya
sejak lama. Muhammad Al Fayyadl pada akhirnya membagi arti dari populisme itu
sendiri menjadi dua, yaitu populisme yang selama ini kita kenal sebagai pola
berpolitik berdasarkan popularitas dan populisme yang berarti gerakan
kerakyatan[1][1].
Dalam kata lain, Populisme dalam arti sesungguhnya ialah gerakan yang
menjadikan rakyat sebagai subjeknya. Tapi apakah benar Populisme itu gerakan
yang menempatkan rakyat menjadi subjek utama? Ernesto Laclau menyebutkan bahwa
‘rakyat’ dalam populisme belum benar-benar spesifik dan mempunyai arti khusus
yang membuat kita berpendapat bahwa populisme sebagai bentuk gerakan progresif.
Tetapi, baik kaum liberal maupun progresif sangat mencurigai populisme karena
tidak jelasnya arti dari gerakan tersebut.
Selanjutnya, Laclau membuat konsep menarik terkait
konsep rakyat dalam populisme, seperti yang ditulis oleh al Fayyadl:
“… Di sini Laclau
mengajukan suatu konsepsi yang menarik, bahwa “subjek” itu belum ada, dengan
kata lain, ia menunggu untuk diciptakan. Populisme memiliki subjeknya pada
populus, pada rakyat yang menjadi syarat material (dan kategoris) bagi
keberadaannya, namun populus itu sendiri belum ada. Ia butuh diciptakan. Maka,
pertanyaan besar yang mengganggu populisme adalah: “Bagaimana mengkonstruksi
‘rakyat’? (How to construct ‘the people’?). Dengan kata lain, bagaimana
mengkonstruksi “rakyat” yang spesifik (‘the’ people), rakyat yang tidak sekadar
rakyat, rakyat yang memiliki, dapat kita katakan, agenda-agenda kerakyatan yang
jelas dan mampu menundukkan elite populis tersebut ke dalam tekanan untuk
mewujudkan agenda-agenda tersebut.”[2][2]
Dalam beberapa penjelasan lain, populisme dikenali
melalui ciri yang khas melekat ketika konsep tersebut menjadi praksis dalam
strategi dan ideologi politik. Sebagai strategi politik, populisme berarti
gerakan yang melegitimasikan dirinya sendiri sebagai bagian dari lapisan
rakyat, sehinga antara gerakan dengan rakyat tersebut tidak terpisahkan satu
sama lainnya. Sedangan sebagai ideologi, populisme mempunyai arti yang sama
dengan gerakan kiri, yaitu menentang rezim status quo beserta seluruh
kebijakannya yang dinilai anti rakyat[3][3]
Dari penjelasan diatas, kita dapat menyimpulkan dua
hal. Pertama, populisme adalah gerakan kerakyatan yang belum mempunyai konsep
rakyat yang jelas. Abstraknya pengertian populisme tersebut (terutama mengenai
konsep rakyat) membuat populisme mudah untuk dipelintir oleh segelintir orang.
Misalnya gerakan dari Jokowi yang mengambil hati rakyat dengan membuat
pencitraan dimana-mana. Populisme Jokowi pada akhirnya bergeser menjadi elite populis
yang menempatkan rakyat dalam posisi yang sekunder (atau lebih parahnya lagi,
rakyat menjadi objek dari elite populis tersebut). Kedua, populisme adalah
gerakan anti status quo rezim yang berkuasa. Kita bisa mengambil contoh gerakan
Narodnik yang berkembang di Rusia pada akhir abad 19 dan terorisme kiri ala
Baader-Meinhoff.
Kembali dalam diskusi saya bersama kawan Josman. Dari
pengertian diatas, saya berani menyimpulkan bahwa gerakan populis di Bandung
sangatlah berbahaya. Gerakan populis di Bandung mengambil coraknya, yaitu
strategi politik dalam merebut hati rakyat sehingga gerakan tersebut bisa
bertransformasi menjadi gerakan elite populis. Sekilas memang dua kata tersebut
sangat bertentangan, hal itu lumrah karena populis sendiri berasal dari bahasa
Romania: populus yang berarti rakyat dan elite sendiri dalam bahasa Inggris
berarti barang dagangan yang mempunyai keutamaan khusus. Dalam perkembangannya,
kata elite bergeser maknanya menjadi kelompok sosial yang mempunyai pengaruh
dalam masyarakat. Secara terminologi, elite populis berarti kelompok sosial
yang mempengeruhi masyarakat untuk memenuhi tujuan politiknya[4][4].
Kita bisa merujuk pembagian tipe elite menurut Vilfredo Pareto, yaitu elite
spekulator yang merupakan para manipulator atau pembaharu, serta elite rentier
yang merupakan para konservatif dan penguasa. Merujuk dari pembagian tipe elite
tersebut, elite populis selalu memainkan peran spekulator dalam circulation of
elite.
Menurut saya, Elite populis sendiri mempunyai beberapa
tujuan dalam memainkan perannya sebagai elite rentier, yaitu mengambil hati
rakyat agar rakyat bersimpati kepada kelompok elite tersebut, mempengaruhi
pergerakan rakyat agar rakyat memenuhi kepentingan kelompok elite tersebut,
serta menguasai popularitas di kalangan rakyat sehingga kelompok elite tersebut
dapat memperoleh prestige yang dihormati oleh rakyat. Tujuan-tujuan ini saya
dapat dari realita yang terjadi di Indonesia, khususnya Bandung. Dalam
geopolitik Indonesia, kita mengenal Jokowi dan Prabowo yang memainkan wacana
populisme pada pemilu 2014 yang lalu. Sedangkan di Bandung, saya mengalaminya
sendiri ketika saya dan aliansi Solidaritas Rakyat untuk Demokrasi (SORAK)
menerjunkan diri untuk bergabung bersama rakyat di Kelurahan Kebon Jeruk,
Kecamatan Andir (samping Stasiun Bandung) dalam melawan PT. KAI yang telah
menggusur mereka. Dalam gerakan aliansi tersebut, adanya elite populis membuat
perjuangan terkesan kompromis, saling mengandalkan, dan tidak terkoordinasi
dengan baik.
Dengan demikian, saya menyimpulkan bahwa populisme
seperti pisau bermata dua. Jika pisau tersebut digunakan untuk membunuh demi
sebuah heroisme sehingga mengenai sasaran yang salah, maka si pengguna pisau
tersebut bersifat elite populis. Sebaliknya, jika pisau tersebut digunakan
untuk memburu para pencuri nilai lebih yang telah menyengsarakan rakyat
pekerja, maka si pengguna pisau tersebut bersifat revolusioner.
[1][1] Muhammad Al Fayyadl dalam artikel Gerakan Kiri,
Populisme, dan Elite Populis yang ditulis pada 19 April 2014.
[3][3] Lihat Varieties of Populism: An Analysis of The
Programmatic Character of Six European Parties karya Jasper de Raadt, David
Hollanders, dan Andre Krouwel. Lihat juga Reza Gunadha dalam artikelnya di
Indoprogress: Bahaya Politik Populis di Indonesia yang ditulis pada 30
Oktober 2012.
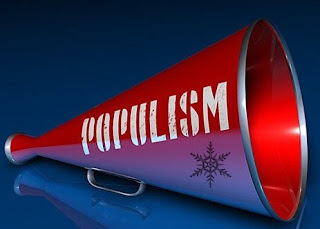



0 comments:
Post a Comment